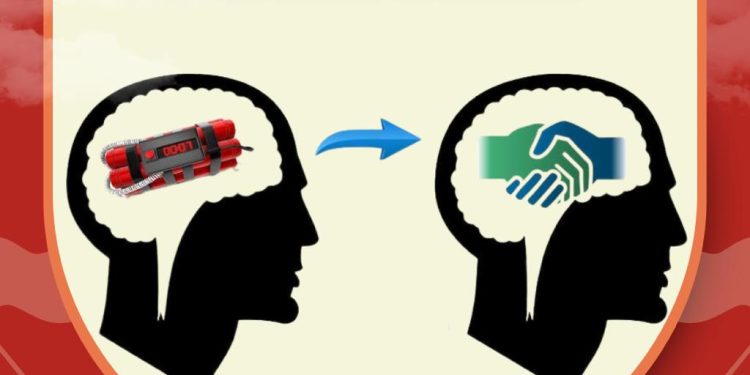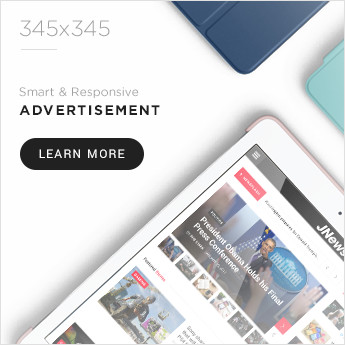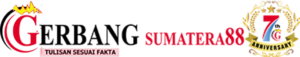Oleh: Teddy Rachesna – 3202408072
Di tengah gempuran konten kebencian di media sosial dan narasi intoleransi yang makin membanjiri ruang publik, kisah Umar Patek, mantan narapidana kasus Bom Bali 2002-yang kini menjadi barista dan membuka kedai kopi, tiba-tiba menjadi headline. Sebagian publik memujinya sebagai bukti keberhasilan program deradikalisasi, sebagian lain justru geram dan curiga: apakah kita terlalu mudah memaafkan? Apakah cukup dengan menjadi “baik” di permukaan, seseorang yang dahulu menanam teror bisa dikatakan sudah berubah?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar ekspresi kebingungan, melainkan tanda keprihatinan kolektif terhadap sebuah realitas yang jauh lebih kompleks.
Terorisme bukan hanya produk dari ideologi radikal semata, tetapi juga merupakan simptom dari sistem sosial-politik yang gagal menyediakan keadilan, keteladanan, dan masa depan. Ia adalah hasil dari akumulasi rasa frustrasi, keterasingan, dan kegagalan dalam pendidikan nalar.
Di Indonesia, deradikalisasi berkembang seiring lonjakan aksi terorisme pascareformasi. Menurut Jenderal Polisi (Purn.) Tito Karnavian, dalam bukunya Indonesian Top Secret (2014), pemahaman terhadap psikologi pelaku lebih penting dari sekadar penindakan hukum. Tito mengembangkan pendekatan multidimensional: gabungan antara pendekatan keras berbasis hukum dan pendekatan lunak yang berbasis pemahaman teologis, sosial, dan kultural. Ia menulis, “Teroris tidak muncul dari ruang hampa. Mereka adalah produk dari jaringan, ideologi, dan rasa keterasingan sosial.”
Tokoh lain seperti Komjen (Purn.) Boy Rafli Amar, saat memimpin Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), mendorong transformasi pendekatan deradikalisasi menjadi lebih partisipatif. Ia menekankan pentingnya kontra-narasi dan kontra-propaganda dengan melibatkan pemuka agama, guru, influencer muda, hingga mantan narapidana terorisme itu sendiri. Strategi ini berupaya menyeimbangkan keamanan nasional dengan keadilan sosial.
Namun, pertanyaannya kemudian: seberapa dalam deradikalisasi menyentuh akar persoalan? Seberapa siap masyarakat untuk menyambut eks napiter kembali ke kehidupan sosial? Apakah program reintegrasi sosial pasca-deradikalisasi hanya menjadi jargon birokratis tanpa pendampingan berkelanjutan?
Kasus Umar Patek dapat dibaca dari banyak lapisan. Ia bisa menjadi simbol harapan: bahwa bahkan pelaku ekstrem bisa kembali menjadi warga biasa. Tetapi ia juga bisa menjadi etalase yang digunakan negara untuk membuktikan keberhasilan semu di tengah realitas yang belum tertangani. Dalam kenyataannya, banyak eks napiter yang masih hidup dalam keterasingan sosial, dipantau aparat tanpa pendampingan psikologis yang memadai, dan mengalami kesulitan ekonomi karena stigmatisasi publik yang akut.
Jika proses reintegrasi tidak didesain dengan pendekatan manusiawi, maka eks napiter justru rentan mengalami “relapse ideologis”—kembali kepada jejaring kekerasan karena merasa ditolak, dikhianati, dan diasingkan.
Dalam laporan BNPT (2023), disebutkan bahwa masih ada eks napiter yang kembali terlibat dalam jejaring radikal, bahkan setelah mengikuti program deradikalisasi formal. Ini menunjukkan bahwa deradikalisasi tidak cukup berhenti pada deklarasi atau pelatihan singkat. Ia harus menjadi gerakan sosial berkelanjutan-melibatkan negara, masyarakat sipil, akomunitas agama, dan sektor swasta dalam membangun ekosistem penerimaan dan rehabilitasi.
Intoleransi hari ini tidak lahir sendirian. Ia tumbuh subur di tengah kemiskinan literasi, polarisasi politik, serta pembiaran terhadap ujaran kebencian. Sekolah dan kampus yang mestinya menjadi ruang kritis justru menjadi ladang infiltrasi ideologi eksklusif. Survei PPIM UIN Jakarta (2020) menunjukkan bahwa sebagian besar guru dan mahasiswa memiliki kecenderungan intoleran terhadap kelompok minoritas agama dan paham yang berbeda. Celakanya, intoleransi ini seringkali dipoles dengan dalil keagamaan.
Media sosial, dengan algoritmanya yang mendorong keterlibatan emosional ekstrem, turut memperparah keadaan. Ketika konten provokatif mendapat lebih banyak jangkauan dibanding narasi damai, maka perang opini bukan lagi soal benar atau salah, tetapi soal siapa yang paling keras berteriak.
Sementara itu, elite politik kerap kali mempermainkan isu identitas demi keuntungan elektoral. Sentimen keagamaan dijadikan alat mobilisasi massa, bukan untuk perbaikan sosial, melainkan sebagai kendaraan kekuasaan. Dalam konteks ini, munculnya terorisme bukan hanya hasil dari kekeliruan ideologi, tapi juga dari sistem politik yang permisif terhadap kebencian.
Melawan radikalisme dan intoleransi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan militeristik semata. Ia harus dibarengi dengan strategi kebudayaan yang mendalam dan konsisten. Pendidikan kritis sejak dini menjadi kunci. Anak-anak harus dibiasakan untuk bertanya, meragukan, dan berdialog—bukan sekadar patuh dan menelan dogma.
Para guru dan tokoh agama perlu didukung dan dilatih untuk menjadi agen moderasi, bukan penguat polarisasi. Pemerintah daerah harus berani menyisir kurikulum dan materi dakwah dari konten yang menyuburkan kebencian. Di saat yang sama, media harus bertanggung jawab menciptakan ruang publik yang sehat dan rasional.
Lebih dari itu, keluarga—sebagai komunitas terkecil—perlu menjadi tempat pertama anak belajar toleransi. Sebab banyak bibit radikalisme tumbuh bukan di pesantren atau kampus, tapi di ruang makan dan grup WhatsApp keluarga.
Merawat nalar sejuk di tengah arus kebencian bukanlah tugas jangka pendek. Ia bukan sekadar tugas polisi, BNPT, atau Kementerian Agama. Ia adalah proyek kolektif bangsa.
Kita boleh senang melihat Umar Patek berubah, tapi jangan sampai puas dengan simbol semata. Perubahan sejati adalah ketika sistem yang melahirkan radikalisme juga ikut dibenahi: dari cara kita mendidik, berbicara, memilih pemimpin, hingga cara kita menanggapi perbedaan.
Kita harus memastikan bahwa generasi berikutnya tidak harus melalui jalan berdarah yang sama untuk menemukan makna damai.
Bahwa mereka dapat tumbuh dengan nalar terbuka, empati mendalam, dan kesadaran bahwa perbedaan bukan ancaman—melainkan kekayaan yang perlu dirawat.
Dan jika perubahan itu dimulai dari secangkir kopi yang diseduh dengan hati, maka semoga kita tak berhenti hanya pada secangkirnya. Tapi terus menanam benih-benih damai di setiap sudut negeri ini….
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku dan Artikel Jurnal
Karnavian, M. T. (2014). Indonesian top secret: Membongkar aktivitas terorisme di Indonesia. Jakarta: Kompas.
Azis, I. (2021). Paradigma penanggulangan terorisme berbasis pendekatan humanis dan integratif. Jakarta: Lemdiklat Polri.
Amar, B. R. (2022). Strategi komunikasi kontra narasi terorisme di Indonesia. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Press.
Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta. (2020). Survei nasional potensi intoleransi dan radikalisme di sekolah dan kampus. Jakarta: PPIM UIN.
Wahid Foundation. (2018). Survei nasional: Sikap keberagamaan dan potensi intoleransi sosial keagamaan di kalangan Muslim Indonesia. Jakarta: Wahid Foundation.
Setara Institute. (2022). Indeks Kota Toleran 2022. Jakarta: Setara Institute for Democracy and Peace.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). (2023). Laporan tahunan BNPT: Penanggulangan terorisme dan radikalisme. Jakarta: BNPT RI.
International Crisis Group. (2016). Indonesia's Lamongan network: How East Java, not Bali, became the epicentre of jihad (Asia Report No. 288). Brussels: ICG.
Yusof, M., & Mohamad, M. (2019). Radicalization and counter-radicalization in Southeast Asia: The case of Indonesia. Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, 14(1), 36–52.